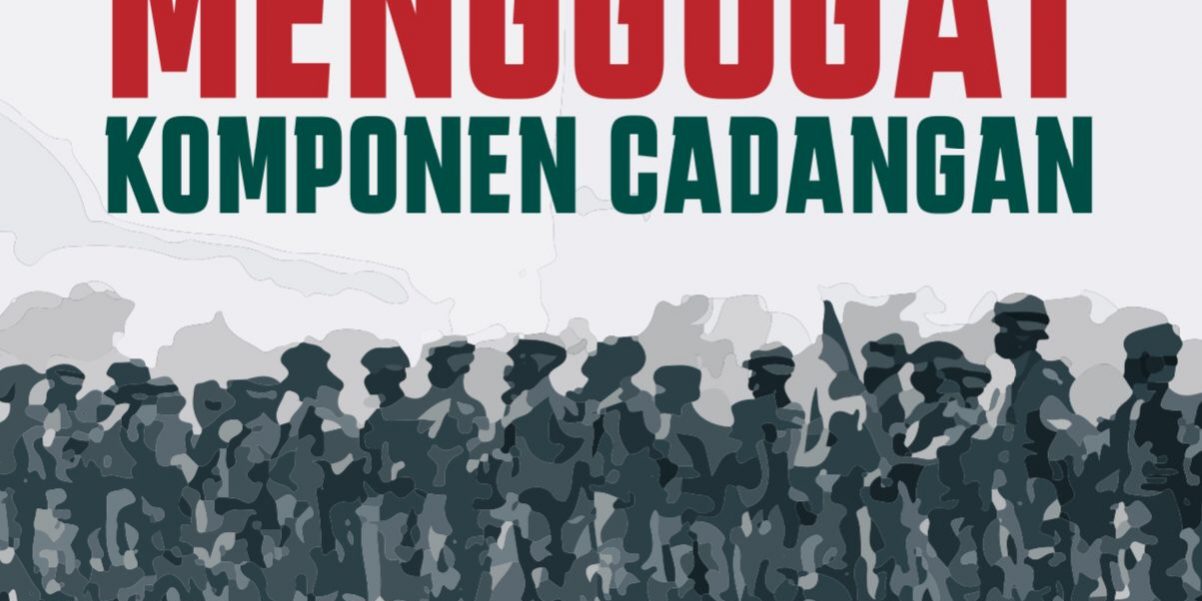Pada tanggal 31 Oktober 2022 Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan terhadap perkara Judicial Review UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN yang dimohonkan oleh Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. Dalam putusannya MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap putusan ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, Demokrasi dan HAM.
Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil serta dalam beberapa pertimbangan gagal memahami maksud konstitusi. Pertama, MK dalam pertimbangannya sendiri mengakui bahwa definisi ancaman dalam UU PSDN kabur dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kendati demikian, alih-alih membatalkan pasal tersebut, MK justru pemerintahan pembentuk undang-undang untuk merevisi pengaturan tersebut melalui revisi UU PSDN yang telah masuk Prolegnas yang sejatinya tidak dibenarkan dalam konteks hukum.
Kedua, dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa dalam hal penetapan Komponen Cadangan Manusia, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sarana dan Prasarana Nasional (SARPRASNAS) harus demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Meski argumentasi MK telah benar, MK seolah tidak berani menyatakan bahwa penetapan sepihak yang dapat dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) sebagaimana diatur dalam UU PSDN adalah keliru, tidak demokratis dan berpotensi melanggar HAM. Bagaimana mungkin penetapan sepihak Menhan tanpa adanya kesukarelaan oleh pemilik SDA, SDB, dan SARPRASNAS tanpa adanya mekanisme penolakan dapat dikatakan demokratis dan sesuai dengan HAM.
Ketiga, petimbangan MK yang menyatakan bahwa UU PSDN sudah mengakomodir prinsip Conscientious Objection oleh karena pemerintah tidak mewajibkan warga negara mengikuti komponen cadangan adalah ngawur dan sama sekali tidak memahami pokok permasalahan. UU PSDN memang benar tidak mewajibkan warga negara untuk mengikuti Komcad, akan tetapi UU PSDN tidak sama sekali memberikan mekanisme penolakan (prinsip Conscientious Objection) bagi warga negara apabila telah mengikuti Komcad dan malah terhadap Conscious Objector (Komcad) justru diancam dengan hukuman pidana. Kami menilai Mahkamah hanya mengulang preseden buruk UU No. 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer, dalam Penjelasan Pasal 11 dinyatakan bahwa “Dalam pasal ini belum dimuat ketentuan mengenai kemungkinan pembebasan dari golongan tertentu yang juga terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan yang tidak bersedia menjadi prajurit (secara sukarela maupun wajib) karena hal itu adalah bertentangan dengan kepercayaan yang dianutnya (“principiel dienst weigeraars”); Ketentuan-ketentuan tentang hal ini perlu diatur dalam Undang-undang tersendiri.
Lebih dari itu, terhadap pemilik SDA, SDB dan SARPRASNAS sifatnya wajib oleh karena penetapannya yang sepihak oleh Menhan atau tidak sama sekali mengakomodir Conscientious Objection.
Keempat, dalam pertimbangannya MK mengakui bahwa sistem peradilan militer harus direformasi sebagaimana amanat reformasi yang tertuang dalam Tap MPR No. VII tahun 2000 yang salah satu pokoknya membagi kekuasaan peradilan sipil dan militer serta juga memerintahkan TNI untuk tunduk pada kekuasaan peradilan umum (sipil) dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Kendati berpendapat demikian, MK dalam putusan tidak konsisten dengan tidak membatalkan pasal yang mempidanakan Komcad (sipil) dalam Peradilan Militer.
Kelima, dalam pertimbanhan MK mengakui bahwa dalam hal untuk menghadapi ancaman militer TNI merupakan komponen utama, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sebagaimana Pasal 7 UU Pertahanan Negara. Konsekuensi dari pernyataan tersebut seharusnya komponen cadangan yang dibuat Kemhan seharusnya hanya ditujukan untuk kepentingan membantu komponen utama yakni TNI dalam pertahanan negara dalam rangka menghadapi ancaman militer atau kemungkinan perang dengan negara lain. Sedangkan untuk menghadapi ancaman selain ancaman militer, kementerian pertahanan tidak tepat untuk membentuk komponen cadangan, karena komponen utama menghadapi ancaman selain ancaman militer adalah lembaga di luar bidang pertahanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU Pertahanan Negara. Dengan dasar pertimbangan ini hakim MK harusnya mengabulkan gugatan pemohon agar komponen cadangan digunakan untuk hadapi ancaman militer saja (perang) dan tidak untuk ancaman non militer dan hibrida. Namun MK malah menolak gugatan pemohon padahal dasar pertimbanganya sudah jelas.
Keenam, Mahkamah Konstitusi juga kacau dan keliru dalam dasar konseptualnya di dasar pertimbangannya dan keputusannya. Salah satunya MK menyebutkan bahwa Polisi adalah masyarakat sipil sehingga sama dengan ormas dan karenanya diklasifikasikan sebagai komponen pendukung sehingga pengaturan UU PSDN sudah benar. Padahal dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” Dalam negara demokrasi polisi bukan masyarakat sipil tetapi institusi sipil dan alat negara untuk menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Dengan demikian, pertimbangan dan putusan MK yg menyebutkan bahwa Polisi adalah bagian masyarakat sipil adalah sesat pikir.