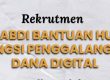20 Oktober 2025 jatuh sebagai penanda satu tahun jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Dalam momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, LBH Jakarta memandang perlu untuk melakukan evaluasi dan refleksi mendalam atas arah kekuasaan negara saat ini. Janji-janji perubahan yang dulu disuarakan apakah sudah menghasilkan kebermanfaatan bagi Rakyat?
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah otoritarianisme, kondisi ini mirip dengan apa yang diuraikan oleh Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die, mengenai 4 indikator kunci perilaku otoriter. Yaitu adanya, 1) penolakan terhadap aturan main demokrasi, baik melalui tindakan maupun regulasi; 2) penyangkalan legitimasi oposisi dengan menyebut gerakan protes “dibiayai” dan “antek asing”;3) toleransi kekerasan melalui represi aparat negara dalam menghadapi demonstrasi, dan 4) membatasi kebebasan sipil, termasuk media melalui pembatasan demonstrasi, kriminalisasi kritik dalam medium digital, dan serangan hukum pemerintah terhadap masyarakat dan media.
Wajah rezim hari ini tidak jauh berbeda dengan wajah otoritarian sebelum reformasi, karena hanya dibungkus dengan wajah populisme baru. Otoritarianisme ini pada akhirnya menjelma dalam berbagai kebijakan, mulai dari perluasan peran militer dalam ruang sipil, kebijakan ekonomi yang melanggengkan ketimpangan, hingga kekuasaan yang memoles dirinya dengan warna hijau palsu, menggaungkan transisi energi dan kemandirian pangan, namun justru membuka pintu bagi perampasan ruang hidup dan keamanan bermukim rakyat atas nama “pembangunan hijau”.
Maka, sebagaimana mandat rakyat yang dititipkan kepada Prabowo-Gibran untuk membangun Indonesia, rakyat pula lah yang wajib mengevaluasinya. Berikut adalah beberapa catatan kritis terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:
Pertama, kekerasan dan represi negara menjadi pilihan dalam membungkam kebebasan ruang sipil. Menilik kembali delapan butir visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertajuk Asta Cita, tidak ditemukan satu pun komitmen eksplisit untuk menjamin kebebasan ruang sipil. Tak ada penyebutan tentang penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, maupun jaminan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Tidak ada juga tekad untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu ataupun membangun sistem akuntabilitas negara terhadap kekerasan aparat.
Ketiadaan komitmen ini bukanlah suatu kebetulan. Ia merupakan cermin dari watak rezim yang sejak awal tidak melihat demokrasi dan kebebasan sipil sebagai pondasi kekuasaan, melainkan melihatnya sebagai suatu ancaman. Dalam setahun terakhir, represi terhadap ruang sipil menjadi praktis yang sistematis. Kami mengambil contoh momen aksi sepanjang tahun 2025, data dilapangan menunjukan bahwa:
- Dalam brutalitas aparat dalam membubarkan aksi ditemukan pola kekerasan berupa penggunaan gas air mata dan water cannon, pemukulan dan penendangan, serta penangkapan sewenang-wenang.
- Berdasarkan temuan LBH-YLBHI dalam Aksi #TolakRUUTNI: tercatat 191 korban kekerasan yang tersebar di 14 wilayah.
- Berdasarkan data Komnas HAM dalam Gelombang aksi 28 – 29 Agustus 2025: tercatat 10 orang korban jiwa serta terjadi lonjakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat di beberapa wilayah.
- Dalam kasus kriminalisasi terhadap peserta aksi juga ditemukan pola serupa yaitu intimidasi pra aksi, penangkapan tanpa surat perintah, interogasi berjam-jam dan penjeratan pasal karet pasca aksi.
- Berdasarkan temuan data LBH-YLBHI dalam Aksi #TolakRUUTNI: tercatat 153 orang ditangkap di 8 wilayah berbeda.
- Berdasarkan temuan LBH Jakarta dalam Aksi Mayday 2025: tercatat 14 orang yang terdiri dari peserta aksi dan tim medis dikriminalisasi.
- Berdasarkan data yang dihimpun oleh TAUD dalam Gelombang Aksi 28-29 Agustus 2025: tercatat 1.240 orang ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
- Kasus pembungkaman digital Pemantauan akun aktivis, doxing, penyitaan ponsel, spam panggilan, pasal karet (Pasal 27 UU ITE, Pasal 160 KUHP dan Pasal 207 KUHP), serta penghapusan konten kritis di media sosial.
- Berdasarkan temuan data SAFEnet tertanggal 25 Agustus – 5 September 2025: tercatat 65 kasus pelanggaran hak digital terkait demonstrasi.
Dari hasil pemantauan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bersama LBH Jakarta, Komnas HAM, dan Jaringan masyarakat sipil lainnya, Polri menjadi aktor paling dominan dalam berbagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi sepanjangan 2019-2024 yakni berjumlah 4.555 aduan dan tren ini terus berlanjut hingga tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dapat dilihat dengan adanya temuan TAUD penangkapan disertai kekerasan saat May Day 2025.
Dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pola kekerasan ini tidak hanya berlanjut, tetapi semakin terstruktur dan dilegalkan. Aparat kepolisian kerap membubarkan aksi damai dengan alasan administratif seperti “tidak berizin” atau “mengganggu ketertiban umum”, padahal dalam Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum hanya mewajibkan pemberitahuan, bukan izin.
Selain Polri, TNI pun turut terlibat dalam sejumlah aksi represif, khususnya pada momentum demonstrasi besar seperti #TolakRUUTNI dan #ReformasiDikorupsi. Pelibatan prajurit militer aktif dalam pengamanan aksi sipil merefleksikan semakin kaburnya batas antara fungsi pertahanan dan keamanan domestik, sekaligus menandakan kembalinya wajah militerisme dalam ruang publik.
Kedua, menguatnya militerisme di berbagai sektor sipil dan politik adalah hal normal yang terjadi selama 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 27 tahun lalu, reformasi 1998 menghasilkan runtuhnya doktrin dwifungsi ABRI untuk memberhentikan militerisme pada sektor sipil maupun sektor politik. Akan tetapi, pemerintahan Prabowo-Gibran secara aktif berusaha membalikan fakta tersebut dengan pembahasan RUU TNI dalam ruang tertutup dan pengesahannya yang tergesa-gesa. Upaya judicial review atas UU TNI terus dilakukan meskipun penolakan permohonan uji formil oleh Mahkamah Konstitusi pada September 2025. UU TNI digaungkan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi di tengah seruan “Kembalikan militer ke barak!” oleh masyarakat luas. Selain itu, perwira aktif juga hadir menempati tempat duduk strategis program unggulan Prabowo-Gibran seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan sektor ketahanan pangan untuk menyokong Makan “Bergizi” Gratis atau MBG. Fenomena keracunan makanan yang dialami lebih dari 11.500 anak sekolah mendorong LBH Jakarta dan lembaga lainnya untuk meluncur MBG Watch. Padahal, program unggulan Prabowo-Gibran ini telah memangkas anggaran pendidikan dan juga kesehatan. Posisi strategis yang ditempati o
leh perwira aktif adalah salah satu dari sekian banyaknya faktor kegagalan MBG.
Tidak berhenti di kewenangan TNI, Prabowo-Gibran juga ingin meluaskan kewenangan Polri dengan RKUHAP dan wacana RUU Polri. Apabila disahkannya kedua instrumen hukum tersebut, Polri akan menjadi lembaga superpower dalam sektor penegakan hukum sekaligus memperlemah peran advokat dan pemberian bantuan hukum. Hak masyarakat sipil sebagai pelapor, korban, saksi, dan juga tersangka maupun terdakwa akan melemah. Alih-alih menyempitkan kewenangan Polri, Prabowo-Gibran gigih untuk meluaskannya. Padahal, represifitas Polri terus terjadi dan demonstrasi pada 25–29 Agustus 2025 menjadi salah satu contohnya. Penabrakan Affan Kurniawan dengan truk Brimob menjadi salah satu contoh bahwa Polri telah melakukan extra–judicial killing yang merupakan pelanggaran HAM. Dapat disimpulkan, dengan perluasan kewenangan TNI maupun Polri, janji Prabowo-Gibran saat masa Pemilu yang ingin memperkokoh demokrasi dan HAM hanya fiktif belaka.
Ketiga, maraknya hak atas peradilan yang jujur dan adil dalam hukum acara pidana. Dalam lanskap kekerasan negara satu tahun terakhir, praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang menjadi salah satu pola paling dominan. Namun yang lebih berbahaya, pelanggaran ini tidak hanya bersumber dari perilaku aparat, tetapi juga dari struktur hukum acara pidana yang lemah dan semakin diarahkan untuk mengukuhkan kontrol negara atas warganya.
Secara normatif, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah memuat prinsip fundamental perlindungan hak warga negara. Beberapa pasal kunci yang melindungi warga negara diantaranya: pasal 18 dan pasal 21 KUHAP menjamin bahwa penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah. Pasal 54 dan pasal 56 KUHAP yang menjamin hak atas akses bantuan hukum.
Namun dalam praktik, prinsip-prinsip ini kerap dilanggar secara sistematis. Kami mengambil contoh momen aksi sepanjang tahun 2025, fakta dilapangan menunjukan bahwa:
- Sebagian besar peserta aksi yang ditangkap tidak menerima surat perintah penangkapan.
- Korban tidak diberi akses ke penasihat hukum selama pemeriksaan awal
- Sebagian juga mengalami intimidasi, kekerasan verbal dan fisik bahkan penahanan di luar mekanisme hukum yang sah.
Kini, ancaman hadir kembali karena RKUHAP sedang dalam penggodokan ulang. Alih-alih memperkuat perlindungan hukum, RKUHAP ini justru memperluas kewenangan penegak hukum dan melemahkan posisi warga. Beberapa masalah krusial dalam RKUHAP di antaranya adalah belum adanya standar upaya paksa yang objektif, belum ada mekanisme pengawasan pengadilan (judicial scrutiny) dan forum komplain yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, masalah mengenai peran advokat dan lemahnya hak atas bantuan hukum juga sering kali menjadi masalah dalam penerapan prinsip fair trial.
Pelanggaran terhadap KUHAP ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menggunakan kekerasan fisik dalam membungkam warganya, tetapi juga melalui kekerasan prosedural dengan mematikan mekanisme perlindungan hukum yang mestinya melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan.
Keempat, perlindungan lingkungan hidup dan ekonomi kerakyatan belum menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Satu tahun berjalan kepemimpinan Prabowo Subianto, namun UU Cipta Kerja yang merupakan kebijakan merugikan dari pemerintahan sebelumnya masih belum dicabut. Undang-Undang yang menghilangkan penegakan lingkungan hidup yang semakin bersifat regresi (mundur). Sebagai contoh, terhapusnya norma pengaturan “Izin Lingkungan” dalam UU PPLH yang sengaja diubah menjadi suatu “Perizinan Berusaha” dan dokumen “Persetujuan Lingkungan”. Perizinan Berusaha memiliki kedudukan yang lemah sebagai objek gugatan dalam spirit penegakan lingkungan hidup, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kehilangan wewenangnya untuk mencabut izin.
Dari sini, terlihat dampak yang dihadapi oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti yang dihadapi oleh Warga Pulau Pari di Kab. Kepulauan Seribu. Mereka haus menggugat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan oleh Kepala BKPM karena berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan sosial-ekonomi kerakyatannya.
UU Cipta Kerja juga mempersempit makna partisipasi publik. Sebelumnya dalam Pasal 26 UU PPLH, pengawasan terhadap dokumen Amdal dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Namun sejak UU Cipta Kerja mengubah Pasal 26 UU PPLH dan menghapus dua kelompok masyarakat lainnya dan hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Faktanya, banyak terjadi proses intimidasi apabila masyarakat tidak “yang terkena dampak langsung” tidak menerima suatu Amdal.
Selain hilangnya prinsip non-regresi dalam penegakan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja turut merampas ruang hidup masyarakat yang menghilangkan lahan pertanian masyarakat dalam balutan “kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional” sebagaimana dalam norma Pasal 3 Huruf d UU Cipta Kerja, dengan daya rusaknya terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat. PSN hanya didasari dengan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kondisi ini menimbulkan disharmoni regulasi.
Kelima, masih dijauhkannya warga dari akses keadilan. Rezim perizinan lingkungan yang semula adalah izin lingkungan, namun dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi persetujuan dengan dalih “menyederhanakan” dasar penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. Kondisi tersebut pula yang menyebabkan adanya corak sentralisasi dalam perizinan, mengingat persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Kepala BKPM dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) atau Menteri ESDM yang berkaitan dengan persetujuan kontrak karya di bidang pertambangan. Sehingga mengharuskan masyarakat terdampak atas penerbitan persetujuan lingkungan di daerah harus jauh-jauh menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Kepala BKPM sebagai tergugat berkedudukan di Jakarta. Selain itu, pencarian keadilan melalui jalur Mahkamah Konstitusi juga mengalami kebuntuan. Salah satunya ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon Mahasiswa dalam pengujian formil UU TNI tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum meskipun mereka telah membuktikan adanya kerugian dan kepentingan hukum untuk menjadi Pemohon di permohonan pengujian formil UU TNI. Selain itu, Perkara yang berlanjut, yaitu Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dinyatakan ditolak padahal sudah jelas bahwa tidak ada partisipasi publik yang bermakna serta banyaknya pelanggaran prosedural dalam UU PPP dalam proses pembentukannya.
Keenam, kondisi perlindungan pekerja/buruh rentan yang tidak kunjung direalisasikan. Dalam dokumen “Visi, Misi, dan Program: Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka”, tertulis cita-cita besar agar “semua buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup.” Janji ini kemudian diperkuat kembali oleh Presiden Prabowo dalam orasi May Day 2025 di Monas, di mana ia menyampaikan sederet komitmen politik yang diklaim berpihak pada kaum buruh. Beberapa di antaranya adalah: (1) menghapus sistem kerja outsourcing yang menindas pekerja; dan (2) mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam waktu kurang dari tiga bulan. Namun, lima bulan berselang, janji-janji tersebut terbukti tidak lebih dari retorika simbolik tanpa realisasi substantif. Tidak ada langkah kebijakan konkret yang menunjukkan keberpihakan nyata terhadap buruh.
Pemerintahan Prabowo–Gibran justru melanjutkan rezim hukum perburuhan yang eksploitatif dan pro-pemodal dengan masih meneruskan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja yang sejak awal ditolak oleh gerakan buruh karena menggerus hak-hak dasar pekerja. Janji penghapusan outsourcing yang sempat digaungkan pun kini menggantung tanpa kejelasan arah kebijakan. Ketidakpastian tersebut bahkan mendorong ribuan buruh turun ke jalan pada 28 Agustus 2025 untuk menagih langsung janji Presiden. Narasi yang dibangun pemerintah—bahwa penghapusan outsourcing harus mempertimbangkan kepentingan investor—justru mengulang logika lama: buruh dikorbankan atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, bukan ditempatkan sebagai subjek pembangunan nasional yang bermartabat.
Sementara itu, janji percepatan pengesahan RUU PPRT yang semula diklaim akan rampung dalam tiga bulan setelah May Day, hingga Oktober 2025 masih mandek di DPR tanpa komitmen politik berarti dari pemerintah. Padahal, regulasi ini merupakan simbol perjuangan panjang kaum perempuan dan para pekerja rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan hukum dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi yang selama ini mereka alami di ruang pekerjaan domestik.
Tantangan lain yang luput diperhatikan adalah soal kejelasan payung hukum dan pengaturan mengenai hak-hak pekerja gig (gig worker) dan transparansi pengusaha di sektor informal, yang menyebabkan adanya ambiguitas hak dan kewajiban karena dikotomi hubungan kerja standar dan “kemitraan”. Untuk di Jakarta sendiri, secara berangsur-angsur menjadi kota informal, per tahun 2023 sebanyak 1.838.096 dari jumlah pekerja di Jakarta merupakan pekerja informal (BPS, 2024).
Ketujuh, Kabinet Merah Putih menormalisasi rangkap jabatan dan oligarki. Sejak awal, pemerintahan Prabowo-Gibran disebut kabinet yang gemuk karena jumlahnya yang besar. Alih-alih mengisi tempat duduk dengan orang-orang yang berkompeten dan juga berusaha memenuhi afirmasi 30% keterwakilan perempuan, kursi-kursi tersebut diisi oleh komisaris BUMN. Meskipun MK melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), sampai sekarang masih ditemukan wakil menteri yang merangkap jabatan. Putusan tersebut memberi para wamen batas waktu sampai dengan 2 tahun untuk transisi secara bertahap. Sudah seharusnya para wamen tersebut mundur dari salah satu posisi saat putusan diketok palu dan bukan melihat batas waktu 2 tahun sebagai toleransi untuk merangkap jabatan. Tindakan yang mereka lakukan menggerus profesionalitas menteri sebagai pejabat negara dan mendorong adanya konflik kepentingan terjadi di level yang lingkaran satu kekuasaan presiden. Bahkan, apabila benangnya ditarik lebih lanjut, seharusnya Prabowo-Gibran tidak melantik komisaris BUMN untuk posisi wamen karena sudah jelas dilarang oleh Pasal 23 UU 39/2008.
Demikian uraian catatan LBH Jakarta dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, banyaknya catatan permasalahan menuntut adanya perbaikan wajah pemerintahan baik di level kebijakan maupun tindakan. Ke depannya, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menunjukkan komitmennya untuk menghindari arah kekuasaan yang otoritarian dengan menjaga kebebasan ruang sipil, memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup, menghindari benturan kepentingan, serta menghadirkan perbaikan dan kebijakan yang diharapkan oleh rakyat.
Hormat Kami,
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Narahubung:
Fadhil Alfathan – Direktur
Alif Fauzi Nurwidiastomo – Kepala Bidang Advokasi